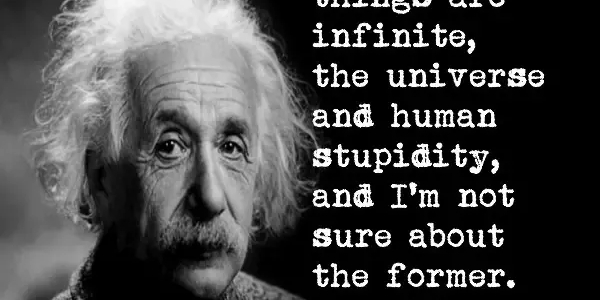Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara
UUD 1945 Pasal 34
Amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 mengisyaratkan kepada negara untuk menjaga agar fakir miskin dan anak terlantar memiliki taraf hidup yang layak. Benarkah sudah benar-benar dijalankan setelah hampir 80 tahun merdeka? Mungkin ada kesalahan tafsir bagi pemegang kekuasaan di negara kita, bahwa fakir miskin dan anak terlantar benar-benar terpelihara sehingga tetap miskin dan terlantar. Negara menjalankan perintah konstitusi secara terbalik. Kenapa kemiskinan tetap terpelihara di negeri ini? Ternyata ada alasan transaksional di dalamnya. Betapa elit politik memanfaatkan kemiskinan ini sebagai komoditas untuk diperdagangkan saat pemilihan umum. Entah itu sebagai calon anggota legislatif, atau bahkan calon presiden sekalipun.
Mengapa saya mengatakan kemiskinan dan kebodohan sebagai komoditas? Analoginya seperti ini, jika rakyat Indonesia sudah hidup makmur, tentu mereka akan lebih cenderung mengedepankan pendidikan sebagai langkah untuk melanggengkan kemakmuran. Jika masih hidup miskin, maka pendidikan bukanlah prioritas untuk diwujudkan karena ada perut lapar yang harus dikenyangkan atau bahkan hanya untuk sekedar terisi. Hanya bagi mereka yang bisa menahan lapar akan menjadikan pendidikan sebagai pintu untuk keluar dari kemiskinan. Apakah semua orang miskin berpikir seperti itu? Tentu bisa dipastikan tidak semuanya. Masih banyak orang miskin entah itu di kota maupun di desa yang lebih mementingkan kondisi ekonomi mapan dibandingkan berpendidikan. Alasannya bisa beragam, tetapi yang paling banyak adalah orang yang sekolah tinggi saja banyak yang menganggur padahal udah menghabiskan waktu untuk menimba ilmu. Itulah akhirnya “kebodohan” jauh lebih mulia dibandingkan tidak punya uang untuk makan.
Apalagi yang menjadi permasalahan utama di Indonesia yang menyebabkan kemiskinan semakin menjadi? Satu hal yang menjadi faktor utama adalah pemerintah tidak memperhatikan dan menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai program utama. Bukan tidak ada program, tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah justru memberikan bantuan sosial dalam bermacam-macam bentuk. Hal ini menjadi dua sisi mata uang dalam pengentasan kemiskinan karena justru mendadak banyak orang yang ingin menjadi miskin agar dapat bagian dari bantuan sosial. Buktinya tetangga saya malah senang dapat bantuan sosial orang miskin, padahal secara ekonomi tidak layak dikatakan orang miskin karena punya dua sepeda motor, punya sawah sendiri, punya banyak ternak, dan punya pekerjaan dengan gaji yang cukup.
Ini yang saya katakan, mengapa kemiskinan tidak berkurang sekalipun sudah banyak program untuk menghapusnya. Bahkan Presiden Jokowi mengeluarkan inpres di tahun 2022 untuk menghapus kemiskinan ekstrim, tapi hanya dalam bentuk angka yang menurun karena standarnya diturunkan sehingga orang yang hampir miskin tidak dianggap miskin, hanya orang yang berpenghasilan Rp. 12.000 per kapita per hari yang dianggap miskin. Padahal Bank Dunia memberikan gambaran bahwa orang miskin adalah berpenghasilan Rp. 38.000 per kapita per hari. Jadi, kalau kawan hanya berpenghasilan di bawah itu, sudah layak dianggap miskin. Jadi wajar kalau klaim bahwa kemiskinan di Indonesia menurun.
Lalu bagaimana dengan kebodohan yang semakin menjadi-jadi? Oke kita definisikan dulu kata bodoh agar jelas. Kata bodoh menurut KBBI adalah sukar mengerti atau tidak cepat menanggapi sesuatu (tidak tajam pikiran). Jadi sudah jelas kan kawan, kalau banyak orang yang memelihara kebodohan agar pikirannya tidak tajam sehingga lambat untuk menanggapi perubahan yang terjadi di negeri ini. Bahkan banyak orang bodoh yang berlagak pintar menggunakan analogi yang jauh panggang dari api. Ketidaktajaman pikiran ini pada akhirnya menjadi celah untuk disusupi pemikiran yang “sesat” hingga kesalahan dianggap hal yang wajar.
Kebodohan sebenarnya bersumber dari turunnya minat baca orang Indonesia. Bisa dilihat dari skor PISA yang setiap tahun mengalami penurunan sejak tahun 2009, hanya sempat naik sedikit di tahun 2015. Apa artinya? Kemampuan kita dalam membaca membuat pemikiran kita juga tidak tegas terhadap informasi dan data yang tidak akurat. Kita justru mudah untuk menelan bulat-bulat informasi hoax yang sengaja disebarluaskan melalui media sosial. Lihatlah juga penggunakan diksi yang lebih banyak sumpah serapah.
Padahal dulu kritik disampaikan melalui kalimat tersirat yang membuka ruang diskursus dan sekalipun ada sumpah serapah tetapi penuh isi. Sekarang isinya hilang tinggal sumpah serapahnya saja. Kenapa bisa begitu? Ya karena lebih banyak orang yang bodoh sehingga yang dijadikan panutan adalah simbol kebodohan. Orang cerdas dan pintar tersingkirkan sendiri karena kebenaran saat ini adalah kesepakatan para orang bodoh tidak ingin diajari oleh kebenaran hakiki.
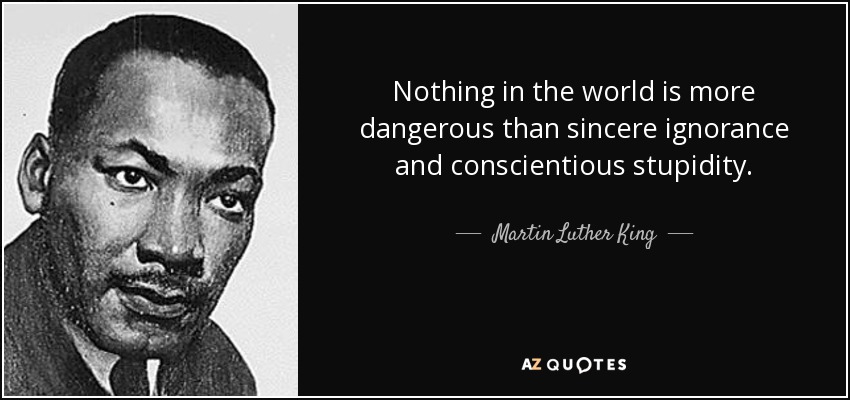
– Martin Luther King-
Lihatlah sekarang, ruang diskursus tidak lagi menjadi pilihan untuk diikuti. Lebih baik melihat orang yang berjoget-joget ria atau menampilkan komedi kebodohan. Lalu apa yang bisa diharapkan jika kebodohan adalah simbol pemersatu? Sudah tentu kehancuran saja yang ditunggu.
Itulah kenapa dua hal ini tetap dipertahankan dan dikembangkan terus menerus untuk menjadi komoditas elektoral setiap lima tahun. Jikalau rakyat makmur dan cerdas, politisi busuk akan kebingungan membuat kampanye yang punya kans menang, rakyat cerdas akan memilih wakil yang cerdas pula dan tentu punya gagasan kuat. Kalau sekarang, gagasan tak perlu, yang jauh lebih penting adalah program transaksional seperti bagi-bagi bantuan beraneka ragam. Angka lebih penting dibandingkan kemakmuran yang terdengar semu. Kenaikan gaji lebih masuk akal dibandingkan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itulah ironi.
Bagaimana menurut kawan sekalian?